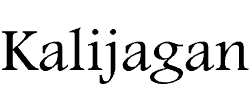Langit tampak hitam
Belum juga terang
Aku sangat takut
Ku sangat pengecut
Mataku terpejam
Dan sangat berharap
Bukan aku yang terbuang
Lampuku temaram, tak tampak terang
Hatiku terdiam, laksana karang
Ketika kucoba mencari-cari
Jalan yang Hilang
Aku tak peduli apa kata orang
Hanyalah untukMu seluruh rinduku
Harus kutemukan sekali lagi
Jalan yang Hilang
Kan kutempuh di kegelapan
Reff:
Hidupku terasa pekat
Nafasku tersendat-sendat
Kulakukan semua itu hanyalah untukMu
Ambillah semua yang Kau mau
Hidupku pun bila perlu
Bolehkan aku menujuMu
Di jalan yang hilang
Di jalanku yang hilang
Begitulah lirik lagu Letto yang kurang familiar di telinga penikmat musik. Saya sendiri pun jarang menjumpai Letto—baik secara band, maupun person— memainkan lagu tersebut di panggungnya. Padahal jika ditinjau secara linguistik, lirik di lagu ini amatlah indah. Jika lagu ini berangkat dari puisi, mungkin lagu ini yang paling puitis diantara lagu-lagu lainnya. Rima yang disuguhkan begitu gurih. Bangunan metafor yang disajikan juga amat banyak ketimbang lagu-lagu Letto lainnya.
Saya akan coba pilihkan frasa yang telah diracik mas Sabrang, sebagai pencipta liriknya, yang tidak hambar untuk kita rasakan. Dari judulnya saja “Jalan yang Hilang”, itu juga menjadi bagian lirik yang menghiasi lagu tersebut. Kemudian frasa “langit tampak hitam”, “lampuku temaram”, “hatiku terdiam laksana karang”, “kan ku tempuh di kegelapan”, “hidupku terasa pekat”, serta “nafasku tersendat-sendat” yang menurut saya gurih.
Demi menjaga kemerdekaan saya dalam usaha mencari, semoga menemukan “Jalan yang Hilang”, maka engkau semua harus ikut bersepakat dengan saya, menganggap “Jalan yang Hilang” sebagai puisi. Sebagai puisi, “Jalan yang Hilang” membuka peluang permaknaan dari beragam sudut pandang, jarak pandang, resolusi pandang dan presisinya. Hal tersebut berbeda jika kita memperbandingkannya dengan berita maupun warta, yang tidak memiliki kemungkinan permaknaan yang beragam sebagaimana puisi. Atas dasar tersebut, saya akan mencoba memasuki “Jalan yang Hilang”, berharap akan menemukan, tidak tersesat dan bisa kembali dengan khusnul khotimah.
Meski tidak sependapat dengan ide Roland Barthes mengenai the death of author, kematian seorang pengarang, namun kali ini saya akan memakai pendekatan yang diusung Barthes. Agar saya lebih bebas membaca tanpa perlu menyangkut-pautkan bacaan dengan penulis. “Jalan yang Hilang” bukan kehilangan jalan atau hilangnya jalan bahkan tersesat. Dari judulnya saja kita sudah diajak berpikir mengenai apa, kapan, dimana dan bagaimana “Jalan yang Hilang” itu. Bicara jalan, definisi jalan di KBBI memiliki sedikitnya 12 arti. Sementara dalam khazanah arab, jalan memiliki sedikitnya 4 kata, sabil, sari’, thoriq dan shirot. Dari banyaknya definisi, saya memilih memakai jalan sebagai shiroth, sebuah perlintasan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebab dari persambungan “jalan” dan “yang hilang”, saya hanya mengingat surat Al Fatihah ayat 6, ihdinas shirothol mustaqim, tuntunlah kami di jalan yang selalu tegak.
Ihdinas shirothol mustaqim adalah suatu dialektika manusia kepada Tuhan, memohon dituntun di jalan yang tegak selama proses hidupnya di muka bumi. Bukan berarti manusia berada di jalan yang hilang, sehingga meminta dituntun. Namun lebih pada romantisme, kerendahan hati manusia dan jaga-jaga sopo ngerti sedang di jalan yang hilang beneran. Selain itu, dunia memanglah ruang yang gelap dan penuh kegelapan, sebagaimana yang disebutkan dalam Qur’an surat Al Hadit ayat 20, Al Insan ayat 27 dan ayat lainnya yang begitu banyak, yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Jadi tidak mengherankan kalau Allah menyuruh manusia yang bersadar menjadi hambanya mengucapkan ihdinas shirothol mustaqim dalam tiap sembahyangnya.
Pemaknaan yang saya pilih itu ditegaskan di baris awal yang berbunyi “langit tampak hitam” sebagai kesadaran bahwa cahaya, petunjuk, tuntunan dari Tuhan belum juga datang. Kemudian ditegaskan di baris berikutnya “belum juga terang”. Apa yang merujuk pada “terang” kalau bukan cahaya? Sebab dua baris tersebut menjadikan baris selanjutnya “aku sangat takut”. Sebab manusia yang memiliki kesadaran cahaya akan menjadi takut jika ia berjalan tanpa adanya cahaya. Dan parahnya lagi kalau sampai pada tahap “ku sangat pengecut” dibaris selanjutnya. Seorang manusia akan menjadi pengecut jika ia tidak mampu melihat apa yang di depannya, sebab ketidakhadiran cahaya, sebab ia tidak tahu apa-apa yang dihadapinya.
Ini menjadi pembuktian pertama, kalau manusia menemukan jalan yang hilang akan mengalami sikap semacam itu. Tapi, bisa jadi ini suatu dialektika manusia kepada Tuhan agar selalu merasa berada di jalan yang hilang. Merasa dholim sebagaimana para nabi yang mengaku dholim, meski sudah maksum, disucikan.
Kemudian pada bait kedua, baris pertama berbunyi “mataku terpejam”. Baris kedua juga menjadi suatu akibat dari sebab bait pertama. Sebab “langit tampak hitam, belum juga terang. Aku sangat takut, ku sangat pengecut” berakibat “mataku terpejam, dan sangat berharap bukan aku yang terbuang.” Saya sendiri, akan mampu berjalan dalam keadaan gelap jika mata saya terpejam. Lalu yang bisa saya lakukan adalah berharap. Berharap tidak kesandung meja, kesandung kursi, kesandung kenangan, pun kesandung mantan. Dalam keadaan semacam itu, saya tidak hanya “berharap” tapi “sangat berharap”. Berhubung ini adalah dialektika antara manusia dan Tuhan, maka yang diharapkan adalah tidak dibuang oleh Allah ke luar wilayahNya. Tapi apa ada, wilayah yang bukan milikNya? Tentu tidak ada. Artinya romantisme masih tersuguhkan dalam dua bait pertama “Jalan yang Hilang”.
Bait ketiga berbunyi “lampuku temaram, tak tampak terang. Hatiku terdiam laksana karang, ketika kucoba mencari-cari jalan yang hilang” masih dalam wilayah sebab-akibat yang berkelanjutan dari bait-bait sebelumnya. Seseorang berusaha memakai penerangan yang diusahakannya, sebab segala peralatan untuk menciptakannya sudah digelar Tuhan di bumi. Setelah menciptakan lampu, manusia masih merasa bahwa cahaya yang diciptakan manusia sendiri hanya pada batas temaram dan tak tampak terang. Setelah berusaha, ternyata belum juga menemukan jalan yang tegak itu, manusia perlu berdiam diri sejenak. Hatinya terdiam laksana karang ketika ia coba mencari-cari jalan yang hilang. Sebab diam sejenak dengan berpikir dan merasa akan membuat manusia siap berjalan lagi dengan bekal pengalaman dan perencanaan yang matang.
“Aku tak peduli, apa kata orang, hanyalah untukmu, seluruh rinduku. Harus kutemukan sekali lagi jalan yang hilang.” Setelah percobaan pencarian pertama yang belum membuahkan hasil. Maka ia tempuh lagi dengan pertimbangan “hanyalah untukMu, seluruh rinduku” serta “aku tak peduli, apa kata orang”. Mengapa hanya untuk Allah lah seluruh rindu? Sebab hanya Dia yang layak diabdi dan dimintai pertolongan sebagaimana iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in. Sebab yang pantas untuk dirindui adalah siapa yang mampu memberi pengayoman, perlindungan dan pertolongan kepada kita, perindu. Engkau pun tahu bahwa rindu itu berat, maka biarlah para hambaNya yang rela menyerahkan kepasrahannya saja yang melakukannya. Maksudnya itu orang-orang yang sudah tidak mempedulikan “apa kata orang”, yang ia pedulikan adalah “apa kata Allah”. Hal yang memberatkan lagi adalah meski tidak menemukan, hamba yang berserah akan selalu berusaha “sekali lagi” sampai benar-benar menemukan “Jalan yang Hilang”. Bait yang sebaris kemudian, menegaskan “Jalan yang Hilang” dengan bunyi “kan kutempuh di kegelapan”. Meski dengan sadar manusia tahu ia di kegelapan, ia tetap menempuhnya.
Dari bait-bait sebelum reff “Jalan yang Hilang”, kita akan menemukan pencapaian stratum dari makhluk, manusia/nas, muslim, hamba/abdun hingga pemimpin/khalifatullah fil ardh. Bait pertama kesadarannya adalah kesadaran makhluk, kesadaran ketidaktahuan, kesadaran pasrah pada sunnatullah. Bait kedua kesadarannya adalah kesadaran manusia, kesadaran action dan memiliki harapan. Lalu bait ketiga, kesadaran yang dipakai adalah kesadaran muslim, kesadaran berijtihad, menemukan suatu penemuan untuk dimanfaatkannya menuju Allah. Di bait keempat, yang tumbuh adalah pencapaian manusia sebagai abdun/ hamba, kesadaran bahwa tidak ada yang patut dirindui selain Allah, tidak ada yang patut didengar kecuali Allah, tidak ada yang patut dituju kecuali Allah. Sementara dibait kelima, manusia sudah pada wilayah khalifatullah fil ardh, wilayah pengetahuan yang tak perlu dipaparkan, wilayah rasa yang tak lagi diruangkan, wilayah menempuh, wilayah manunggaling kawula lan Gusti. Dari lima bait itu, yang saya temukan pemosisian subyeknya semacam itu. Kalau engkau tak percaya, coba rasakan dan pikirkan.
Sementara mengenai reff adalah segala pencapaian manusia sebagai makhluk, manusia, muslim, abdun dan khalifatullah fil ardh. Kelimanya bisa bergerak dinamis, berubah-ubah, kadang jadi muslim, kadang jadi manusia, kadang hanya jadi makhluk, kadang menjadi abdun dan kadang pula menjadi khalifatullah fil ardh. Karena manusia dan jin lah yang diciptakan dalam keadaan dinamis, tidak statis. Manusia dan jin hidupnya juga semacam puisi, multi tafsir, bisa dimaknai dari berbagai macam ruang, waktu, sudut pandang, jarak pandang, resolusi pandang dan presisinya.
Jadi pada intinya, “Jalan yang Hilang” adalah pencapaian manusia menyadari ihdinas shirothol mustaqim dalam hidupnya. Saat engkau merasa butuh tuntunan dariNya, maka hidupmu akan disesuaikan dengan jalanNya. Merasalah sesat, meski tidak sesat. Merasalah dholim meski sebenarnya engkau tidak dholim. Saya rasa, perjalanan menemukan “Jalan yang Hilang” belum berakhir sampai sini. Saya masih menempuh dan belum berakhir. Semoga khusnul khotimah.