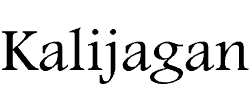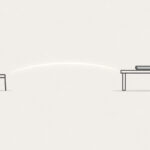“Liring mati sajroning ngahurip, iya urip sajtoning pejah, urip bae selawase, kang mati nepsu iku…”
Mati adalah tidak menyerah pada dunia, tapi menundukkan ego dan kerakusan dalam diri. Nafsu yang ditaklukkan akan terhindar dari kerusakan batin; hidup yang dibingkai kesederhanaan dan kesadaran batin menjadi milik siapa saja yang berani “mati” pada hawa nafsunya.
Kalau manusia mampu mengendalikan dirinya, bukan hanya dia hidup dengan layak, tapi dunia di sekitarnya pun terjaga.
Hari ini kita melihat dunia memberi peringatan keras. Di Sumatera, banjir bandang datang tak mengetuk pintu — menghantam pemukiman, menenggelamkan harapan.
Hutan-hutan yang dulu rimbun kini tinggal cerita; gunung dikeruk untuk tambang, tanah kehilangan daya menahan air. Sungai tidak lagi sabar menerima limpahan kerakusan manusia. Ketamakan itu mati-matian dibungkus—tapi akhirnya terungkap, berujung tragedi.
Jika filosofi Jawa itu berkata: matikan nafsu demi hidup, maka kenyataannya di zaman ini justru terbalik — yang mati bukan nafsu, yang mati adalah nurani. Yang kita kubur adalah kebijaksanaan; yang kita bangkitkan adalah kerakusan tak terpuaskan.
Padahal makna “mati dalam hidup” bukan ajakan untuk menjauh dari dunia. Justru sebaliknya — itu panggilan untuk hadir sepenuhnya. Untuk hidup dengan kesadaran bahwa kita bukan satu-satunya penghuni bumi. Ada pepohonan yang diam tapi menyerap hujan. Ada sungai yang sabar tapi bisa murka. Ada hutan yang setia — sampai akhirnya dijual-sewa manusia.
Ajaran leluhur bukan sekadar warisan kata-kata. Ia kompas moral. Ia cermin: apakah kita masih manusia, atau sudah berubah jadi mesin konsumsi yang tak pandai berhenti?
Banjir di Sumatera hanyalah salah satu bab dari buku peringatan yang makin tebal. Kita bisa saja menuduh hujan terlalu deras, tapi jauh di dalam hati kita tahu: yang meluap bukan air — melainkan kerakusan kita sendiri
“Mati sajroning urip” mengajak kita melakukan hal sederhana tapi sulit:
menempatkan kembali kehidupan di tempat yang benar. Menghidupkan kembali empati — mematikan segala yang membutakan hati.
Karena mungkin, hanya dengan begitu, kita bisa menyelamatkan hidup — bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk anak-anak yang kelak bertanya.