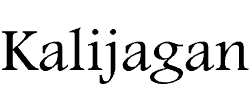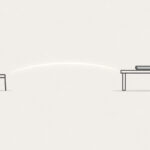Dalam laku hidup orang Jawa, hidayat tidak datang sebagai suara keras yang memerintah, melainkan sebagai bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang mau diam. Di situlah orang mulai mengenal dua lapis petunjuk: hidayat wening dan hidayat jati—keduanya bekerja pelan, tetapi mengubah arah hidup secara mendasar.
Hidayat wening biasanya hadir dalam perkara-perkara kecil, justru ketika seseorang tidak sedang mengejar apa-apa. Misalnya, seorang guru yang sedang lelah dan kecewa karena murid-muridnya sulit diatur. Di tengah kegaduhan kelas dan tuntutan administrasi, ia memilih diam sejenak setelah jam pelajaran usai. Tanpa rapat, tanpa diskusi panjang, tiba-tiba ia merasa perlu mengubah cara mengajar: lebih banyak mendengar, lebih sedikit memarahi. Tidak ada rumus pasti, tetapi hatinya terasa mantap. Itulah wening—ketika keputusan lahir dari kejernihan, bukan dari emosi.
Contoh lain, seorang kepala keluarga yang sedang terhimpit kebutuhan hidup. Ia memiliki kesempatan mengambil jalan pintas yang secara hukum abu-abu namun menguntungkan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melarang. Namun di satu malam yang sunyi, hatinya tidak tenang. Ia tidak bisa menjelaskan alasannya, hanya merasa “ini bukan jalanku”. Ia memilih jalan yang lebih berat, tetapi batinnya lega. Di situlah hidayat wening bekerja: membisikkan batas, tanpa perlu ancaman.
Jika kebeningan seperti itu terus dijaga, dilakoni dalam keseharian, perlahan seseorang digiring menuju hidayat jati. Ini bukan lagi soal satu-dua keputusan, melainkan perubahan cara memandang hidup. Seperti seorang pemimpin sekolah yang awalnya sibuk mengejar prestasi dan pengakuan. Tahun-tahun berlalu, konflik datang silih berganti, hingga ia menyadari bahwa sekolah bukan panggung lomba, melainkan ruang tumbuh manusia. Sejak itu, orientasinya berubah: ia lebih peduli pada guru yang tertekan, pada siswa yang tertinggal, pada suasana yang manusiawi. Ia tidak kehilangan wibawa—justru menemukan maknanya.
Atau seperti seorang petani tua yang tetap bekerja di sawah kecilnya meski hasilnya tak seberapa. Ia tidak iri pada tetangga yang lebih berhasil, tidak pula merasa rendah diri. Ketika ditanya mengapa tetap bertahan, jawabannya sederhana: “Iki sing dadi tugasku.” Ia tahu tempatnya, tahu batasnya, dan tahu perannya. Itulah tanda hidayat jati—kesadaran yang membuat seseorang tenteram berada di posisinya sendiri.
Dalam pandangan Jawa, wening adalah jalan, jati adalah tujuan. Wening menuntun manusia agar tidak terseret oleh nafsu dan kegaduhan sesaat. Jati meneguhkan manusia agar tidak tersesat oleh ambisi dan pembandingan. Tanpa wening, hidup mudah panas dan reaktif. Tanpa jati, hidup mudah kosong meski terlihat berhasil.
Di zaman ketika semua orang berlomba bersuara, mengejar sorotan, dan ingin segera sampai, barangkali yang paling kita perlukan justru keberanian untuk hening. Sebab dari hati yang wening, lahir pilihan-pilihan yang jujur. Dan dari pilihan-pilihan yang jujur itulah, hidayat jati pelan-pelan menemukan jalannya sendiri.