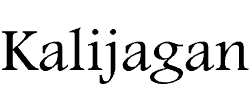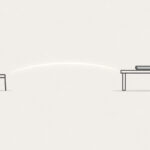Perbuatan baik tidaklah cukup hanya dengan modal niat saja. Sering kali, hal baik yang kita lakukan, belum tentu diterima dengan baik. Seperti kemarin kita disuguhi dengan tontonan kebaikan yang dilakukan seorang pejabat negara, memanggul karung beras untuk diberikan langsung kepada para korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra. Tentunya, hal itu lahir dari niat yang baik, dan juga sebagai wujud rasa tanggung jawab seorang pejabat, untuk membantu meringankan beban penderitaan rakyatnya yang terdampak bencana. Tetapi apa yang terjadi, kebaikan itu malah menambah kekeruhan di tengah-tengah bencana yang melanda. Lebih-lebih, di jagad media sosial kita. Sungguh sangat keruh sekali.
Mengapa keruh? Mungkin, sikap pejabat kita tadi, terlalu begitu cepat menghitung laba-rugi. Terlalu akrab mengubah bencana menjadi komoditas diri. Atau menganggap dunia ini adalah panggung tunggal, sehingga lupa memeriksa niat dan menimbang ulang kembali posisinya sebagai pejabat. Akibatnya, kebaikan yang dilakukannya menjadi keruh oleh hasrat yang selalu ingin tampil dan ambisi ingin menjadi pusat perhatian. Jadi, bukan lagi ketulusan dan keteladanan yang dirasakan, apalagi kewibawaan.
Dalam dunia yang gemar berteriak dan tergesa mencari validasi dan legitimasi, manusia sering terjebak dengan menganggap dirinya sebagai pusat segalanya. Ketika dipuji ia merasa bahwa dunia bergantung padanya, dan ketika diabaikan, ia merasa dilupakan. Padahal kehidupan terus berjalan sesuai ritme-Nya, tanpa menunggu siapapun juga. Ada jutaan kisah perjalanan yang berlangsung bersamaan, ada peran-peran lain yang kita anggap kecil, justru menopang berlangsungnya kehidupan. Ketika seseorang menyadari bahwa keberadaanya tidak akan membuat alam semesta berhenti, maka ia akan belajar kerendahan hati dan tanggung jawab, bukan tuntutan untuk selalu dimengerti dan diistimewakan. Kesadaran ini bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk menempatkan diri secara proporsional.
Maka, perbuatan baik tidak akan sempurna kalau hanya dengan niat saja, akan tetapi dibutuhkan sikap kerendahan hati, rasa tanggung jawab dan kedisiplinan untuk menahan diri. Dengan demikian, seseorang tidak akan berisik berbicara tentang citra kebaikannya, dan juga tidak pernah merasa perlu mengumumkan dirinya sebagai pusat dari segalanya. Namun, dari sanalah aliran kebaikan dan keteladanan mengalir tanpa gemuruh, dan terus memberi kemanfaatan pada kehidupan di sekelilingnya. Inilah jalan sunyi. Jalan yang ditempuh bukan untuk menjauh, namun cara untuk merawat kejernihan aliran kehidupan, supaya bertambahnya nilai kebaikan yang kita kerjakan.
Membantu menghilangkan kesusahan orang lain merupakan perilaku yang terpuji. Sudah semestinya, harus didasari dengan niat yang tulus, serta dibarengi dengan sikap kerendahan hati, agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terjaga dari kekeruhan yang berupa: sikap tinggi hati. Yaitu, sikap merasa paling penting, paling dibutuhkan dan paling bisa segalanya. Kalau di Jawa ada istilah ungkapan: ngono yo ngono, ning ojo ngono. Dari pemahaman itu, lahirlah kebijaksanaan sederhana: lakukan yang terbaik tanpa merasa paling penting. Hiduplah dengan makna bukan dengan keangkuhan. Karena manusia bukan dinilai dari seberapa besar ia dibutuhkan, melainkan seberapa tulus ia memberi manfaat. Meskipun dunia tidak pernah menganggap.
Lantas, bagaimana dengan sikap para pejabat kita selama ini? Tentunya, pertanyaan ini didasari dengan sikap tidak paling merasa benar sendiri.
Wallahu a’lam.