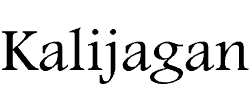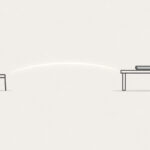Hidup manusia hampir selalu diisi oleh karya. Bangun pagi adalah karya. Menyusun rencana adalah karya. Mengajar, menulis, membangun, bahkan sekadar menyelesaikan tugas harian semuanya adalah bentuk berkarya. Namun anehnya, semakin banyak karya dihasilkan, semakin sering maknanya menghilang. Karya hadir secara fisik, tetapi absen dalam kesadaran batin. Ia selesai dikerjakan, lalu ditinggalkan tanpa sempat ditinggali.
Di sekitar kita, mudah sekali menemukan karya yang “jadi”, tetapi tidak “hadir”. Bangunan cepat rusak, program cepat usai, laporan cepat dilupakan. Ada semangat mengebut pekerjaan, ada dorongan menghabiskan anggaran, ada budaya “yang penting jadi”. Seolah karya hanyalah sesuatu yang harus dilalui, bukan sesuatu yang perlu dijalani. Padahal, karya bukan sekadar hasil. Ia adalah jejak cara manusia berada di dunia.
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: sebenarnya, apa arti berkarya? Berkarya bukan hanya memproduksi sesuatu, melainkan menghadirkan diri secara utuh dalam apa yang diproduksi. Karya yang baik bukan terutama yang cepat selesai, tetapi yang lahir dari kesungguhan hadir. Hadir dengan pikiran, hadir dengan rasa, hadir dengan tanggung jawab. Tanpa kehadiran itu, karya hanya menjadi benda mati yang cepat ditinggalkan waktu.
Seharusnya, berkarya adalah latihan kesetiaan. Setia pada proses, bukan hanya pada tenggat. Setia pada mutu, bukan hanya pada target. Setia pada dampak jangka panjang, bukan sekadar laporan akhir. Berkarya dengan kesadaran bahwa apa yang kita buat hari ini akan hidup lebih lama daripada emosi sesaat kita. Ia mungkin akan digunakan orang lain, diwarisi generasi lain, atau justru menjadi masalah bagi mereka.
Masalahnya, kita sering berpikir jangka panjang hanya pada proyek, bukan pada karya. Proyek dirancang lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun. Tapi karyanya sendiri rapuh, mudah runtuh, mudah ditinggalkan. Akibatnya, kita terus memulai proyek baru untuk menambal karya lama yang gagal bertahan. Energi habis untuk mengulang, bukan untuk merawat. Padahal, karya yang reliabel adalah karya yang memungkinkan manusia berpindah ke kebutuhan yang lebih penting.
Di titik ini, berkarya bukan lagi soal keterampilan, melainkan soal menjadi manusia. Manusia yang berkarya seutuhnya tidak memisahkan tangannya dari hatinya, pikirannya dari tanggung jawabnya. Ia sadar bahwa setiap karya adalah cara ia meninggalkan dirinya di dunia. Bukan meninggalkan nama, tetapi meninggalkan nilai. Bukan meninggalkan kesan cepat, tetapi meninggalkan keajegan.
Menjadi manusia yang berkarya seutuhnya berarti berani melawan budaya “asal jadi”. Berani melambat ketika semua orang mengebut. Berani teliti ketika yang lain terburu-buru. Berani mengatakan “belum siap” ketika sistem hanya ingin “segera selesai”. Ini bukan soal idealisme kosong, tetapi soal kejujuran batin: apakah kita benar-benar hadir dalam apa yang kita kerjakan, atau hanya sedang menyelesaikan kewajiban?
Pada akhirnya, karya menuntut satu hal yang sederhana tetapi berat: kesetiaan. Setia untuk jujur pada kemampuan kita. Setia untuk mengakui keterbatasan kita. Setia untuk merawat apa yang sudah kita buat, bukan hanya memamerkannya saat baru jadi. Karya yang dirawat akan tumbuh. Karya yang ditinggalkan akan membusuk, meski awalnya tampak megah.
Mungkin hidup memang bukan tentang menghasilkan karya sebanyak-banyaknya. Melainkan tentang menghasilkan karya yang bisa kita pertanggungjawabkan, bahkan ketika tak ada yang melihat. Karya yang, saat kita menoleh ke belakang, tidak membuat kita ingin berkata: “seandainya dulu aku lebih sungguh-sungguh.” Dan di sanalah, perlahan, kita pulang. Pulang sebagai manusia yang tidak sekadar sibuk berkarya, tetapi hadir, jujur, dan setia dalam setiap karya yang ia tinggalkan di dunia.